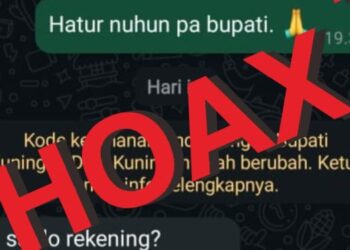Ironisnya, kita sering merasa bersalah bukan karena lalai kepada Allah, tetapi karena telat membalas pesan. Kita cemas bukan karena meninggalkan shalat, tetapi karena unggahan sepi respons. Padahal Allah telah menenangkan manusia sejak lama: “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d: 28). Bukan dengan scrolling. Bukan dengan trending. Bukan dengan viral.
Dari sudut pandang sosiologi, agama algoritma ini menciptakan masyarakat yang tampak ramai tapi rapuh. Semua ingin bicara, sedikit yang mau mendengar. Semua ingin tampil, sedikit yang mau hadir secara utuh. Relasi menjadi dangkal, empati menipis, dan kesunyian justru membesar di tengah keramaian digital. “Kita terkoneksi, tetapi tidak terhubung”.
Namun tulisan ini bukan ajakan untuk membenci teknologi. Ponsel bukan musuh. Media sosial bukan setan. Yang bermasalah adalah ketika hati kehilangan arah. Ketika layar menggantikan nilai, ketika algoritma lebih kita patuhi daripada nurani.
Islam tidak anti zaman. Ia hanya meminta satu hal sederhana namun mendasar, siapa yang kita sembah di dalam hati?. La ilaha illallah bukan sekadar kalimat lisan, tapi pernyataan kemerdekaan batin. Bahwa tidak ada yang lebih layak menguasai jiwa selain Allah.
Kita mungkin tidak bisa mematikan algoritma, tetapi kita bisa mendidik diri. Menjadikan media sosial sebagai alat, bukan tujuan. Menjadikan setiap klik lebih sadar, setiap unggahan lebih bermakna. Mengubah ruang digital dari ladang pamer menjadi ladang manfaat.
Pada akhirnya, agama algoritma hanya akan berkuasa jika kita menyerahkan hati. Selama iman tetap hidup, selama dzikir masih lebih menenangkan daripada notifikasi, selama Allah masih lebih penting daripada pengakuan manusia, maka ponsel hanyalah benda atau alat. Bukan Tuhan.
Dan di tengah dunia yang semakin bising, mungkin bentuk ibadah paling sunyi hari ini adalah, berani berhenti sejenak, menundukkan hati, lalu kembali mengingat untuk apa kita hidup.**(