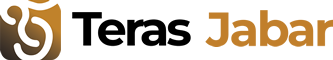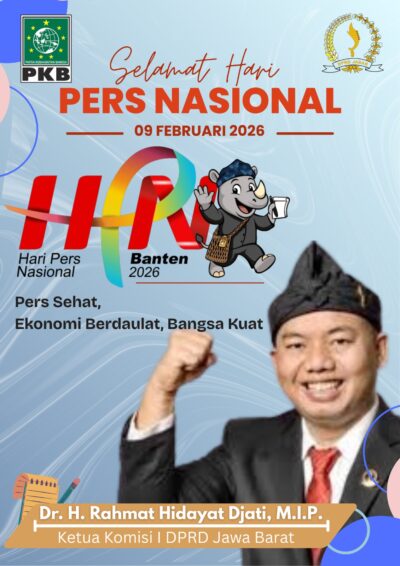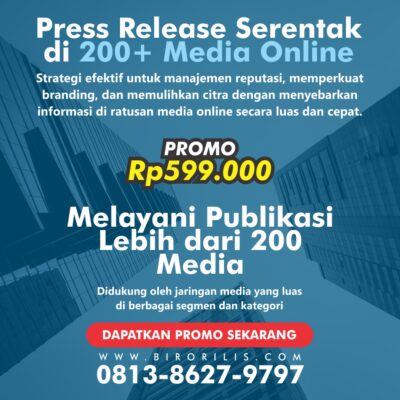Algoritma Kebaikan
Kita sering mengeluh tentang algoritma media sosial. Algoritma membuat kita terjebak pada konten yang sama, kadang hanya mendorong hal-hal yang memancing emosi, bahkan mempersempit wawasan. Namun, bayangkan jika pemerintah kota membangun algoritma kebaikan.
Algoritma ini bukan ditulis dengan kode, melainkan dengan pola komunikasi. Setiap warga Bandung di-“suguhkan” bukan hanya berita konflik atau laporan masalah, tetapi juga informasi yang mencerdaskan, ajakan yang memberdayakan, dan ruang diskusi yang menumbuhkan solidaritas.
Masalah sampah, kemiskinan, kebodohan, dan rendahnya literasi sosial bisa ditangani jika ajakan partisipasi selalu muncul di “beranda kehidupan” warga. Misalnya, bukan hanya pengumuman denda bagi pembuang sampah sembarangan, tetapi konten kreatif tentang cara mengompos. Bukan hanya laporan angka kemiskinan, tetapi kisah inspiratif warga yang berhasil bangkit dengan usaha kecil. Bukan hanya data minat baca, tetapi kisah komunitas yang membuka taman bacaan di gang sempit. Inilah algoritma kebaikan: mengarahkan masyarakat pada optimisme, partisipasi, dan kepedulian sosial.
Membangun SDM: Dari Followers ke Kolaborator
Bandung selalu bangga disebut kota kreatif. Namun kreativitas butuh SDM unggul, dan SDM unggul tidak lahir otomatis. Ia terbentuk melalui komunikasi yang inklusif, literasi yang merata, dan keterlibatan nyata.
Hari ini anak muda Bandung adalah generasi digital native. Mereka tidak puas hanya menjadi penonton. Mereka terbiasa posting gagasan, share keresahan, bahkan menciptakan gerakan sosial dari ruang digital. Pemerintah yang cerdas harus masuk ke ruang digital itu. Bukan hanya hadir dengan akun resmi kaku, melainkan dengan gaya komunikasi yang merangkul, mengajak, dan mendengarkan.
Pemerintah bisa membuat visi kota ibarat caption besar, lalu mengundang masyarakat menambahkan komentar, ide, bahkan kritik. Dengan cara ini, warga bukan hanya followers, melainkan kolaborator.
Ajakan Wali Kota: Dari Bicara ke Teladan
Bagaimana caranya? Salah satunya dengan ajakan yang disertai teladan nyata. Warga tidak mudah percaya pada kata-kata, tetapi mereka akan tergerak bila melihat pemimpinnya melakukan hal yang sama.
Bayangkan jika Wali Kota Bandung, bukan hanya mengimbau soal sampah, tetapi ikut memilah sampah rumah tangga, ikut mengompos di TPS 3R, bahkan mengunggah video pendeknya ke media sosial. Bayangkan jika pejabat turun ke RW, ikut kerja bakti membersihkan sungai, ikut mendongeng di pojok baca, atau ikut mengajar anak-anak di kampung. Itu bukan pencitraan, melainkan praktik komunikasi partisipatif.
Komunikasi semacam ini menular.
Warga merasa ajakan bukan sekadar kata, melainkan contoh. Mereka terdorong untuk meniru, merasa “kalau pemimpin saja mau turun tangan, kenapa saya tidak?” Inilah kunci engagement sejati.