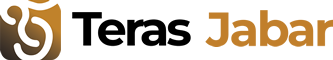Oleh : Subchan Daragana
Di dunia yang serba terbuka hari ini, banyak hal yang dulu membuat kita menunduk kini justru dianggap biasa. Malu yang dahulu menjadi penjaga kehormatan, kini sering disalahpahami sebagai tanda lemah, ketinggalan zaman, atau tidak percaya diri. Padahal, dalam pandangan Islam, malu adalah tanda hidupnya hati. Barangsiapa telah hilang rasa malunya, maka sesungguhnya hati itu sedang sekarat.
Dalam bahasa Arab, kata malu berasal dari “ḥayā’,” yang berakar dari kata “ḥayy,” artinya hidup. Maka, orang yang memiliki rasa malu sejatinya adalah orang yang hatinya masih hidup. Rasulullah ﷺ bersabda: “Al-ḥayā’ min al-īmān” — malu itu bagian dari iman (HR. Bukhari Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa iman dan malu tidak dapat dipisahkan; hilangnya salah satunya menandakan lemahnya yang lain.
Para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa malu bukan sekadar emosi, tapi cahaya yang Allah letakkan dalam hati seorang mukmin agar ia mengenali batas. Ia adalah benteng spiritual yang menjaga manusia dari maksiat, sekaligus mengajarkan adab dalam berhubungan dengan sesama.
Dalam pandangan psikologi modern, rasa malu juga berfungsi sebagai moral compass — penuntun perilaku agar manusia tidak melanggar norma sosial. Ia membuat seseorang sadar diri, menimbang sebelum bertindak, dan belajar dari kesalahan. Dalam tubuh, rasa malu menyalakan kesadaran saraf otonom: jantung berdebar, pipi memerah, tubuh menunduk. Itu semua tanda bahwa jiwa masih peka terhadap kebenaran.
Dari sisi komunikasi, malu berperan sebagai filter moral. Ia mencegah kita berbicara berlebihan, membatasi ekspos diri, dan mengajarkan keheningan yang bermartabat. Sedangkan sosiologi melihat malu sebagai perekat sosial. Ia menjaga harmoni, menumbuhkan rasa hormat, dan meneguhkan nilai-nilai komunitas. Masyarakat yang kehilangan malu biasanya diikuti oleh menurunnya empati, adab, dan rasa tanggung jawab sosial.