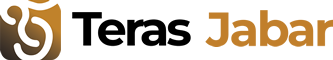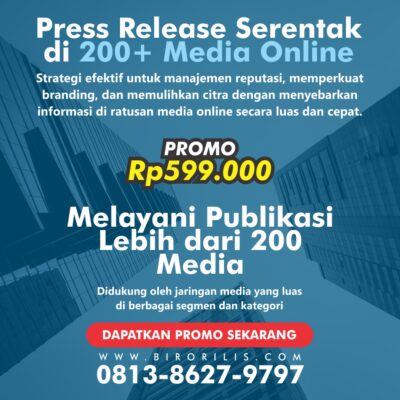Shoshana Zuboff menyebut era ini sebagai surveillance capitalism, ketika setiap klik, pencarian, dan emosi kita dijadikan komoditas. Kita bukan lagi pengguna media, tapi produk dari sistemnya. Di titik ini, manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri.
Dan di tengah ilusi ini, lahirlah paradoks: semakin kita terhubung secara teknologi, semakin kita terputus secara eksistensi. Semakin banyak teman di dunia maya, semakin sunyi di dunia nyata. Semakin kita mencari validasi, semakin kita kehilangan keaslian.
Di Indonesia, fenomena ini tampak nyata di kalangan generasi muda. Mereka tumbuh dalam “budaya layar”, segala hal ada di ujung jari. Mereka kreatif, cepat, adaptif, tapi juga mudah lelah, mudah cemas, dan mudah kehilangan arah.
Kita melihat anak muda yang berani berbicara, tapi sulit mendengar. Aktif di ruang digital, tapi pasif di ruang sosial. Mereka sibuk membangun identitas daring, tapi bingung menjawab siapa dirinya di dunia nyata.
Inilah wajah baru homo digital Indonesia produktif dalam konten, tapi miskin refleksi.
Fenomena yang dulu kita sebut “kecanduan gawai” kini berkembang menjadi “candu validasi”: rasa butuh untuk terus dilihat, disukai, dan diterima. Ini bukan sekadar persoalan teknologi, tapi krisis makna kemanusiaan.
Dalam pandangan Islam, manusia sejati tidak diukur dari seberapa viral, tapi seberapa bermanfaat.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” Artinya, teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Ia seharusnya memudahkan manusia untuk berbuat baik, bukan menenggelamkannya dalam ilusi.